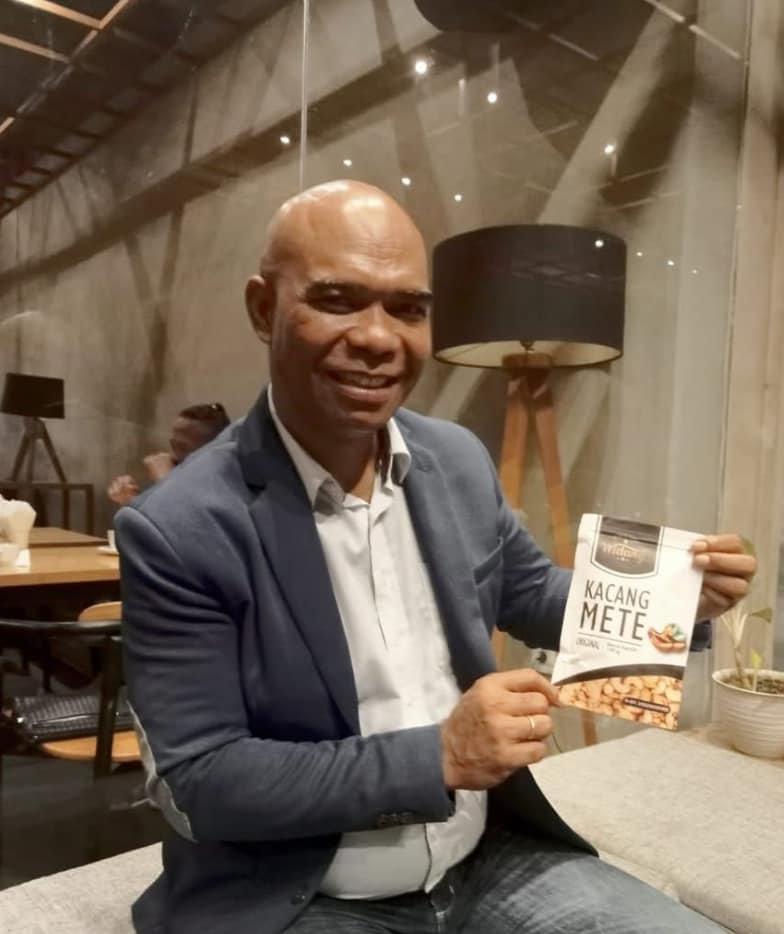TIMIKA,(taparemimika.com) – Dalam beberapa hari terakhir, ruang publik Mimika dipenuhi dengan diskusi hangat bahkan kadang cukup emosional soal konsep “Mimika sebagai Rumah Kita Bersama” yang diperkenalkan sebagai bagian dari visi Smart City. Konsep ini secara resmi menjadi bagian dari arah pembangunan kabupaten, sekaligus sebagai upaya membangun narasi identitas kolektif di tengah masyarakat yang majemuk.
Secara umum, tidak ada penolakan terhadap konsep Smart City itu sendiri. Gagasan kota cerdas yang ditopang oleh digitalisasi layanan publik, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan efisiensi tata kelola pemerintahan justru mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Namun, yang menjadi titik perdebatan adalah frasa “rumah bersama” yang oleh sebagian orang dianggap normatif dan menyatukan, sementara oleh yang lain justru dinilai mengaburkan hak historis masyarakat adat, khususnya Amungme dan Kamoro.
DUA KUTUB PANDANGAN
*Kelompok yang Mendukung
Bagi kelompok ini, Mimika sebagai rumah bersama adalah ajakan moral untuk hidup rukun di tengah keberagaman. Mimika adalah tempat bertemu berbagai suku, profesi, dan latar belakang. Maka, semua yang tinggal dan mencari hidup di sini harus memiliki tanggung jawab kolektif menjaga dan membangun daerah ini. Konsep ini dipandang sebagai cara menyatukan identitas kota secara inklusif, apalagi dalam realitas bahwa Mimika adalah pusat industri dan magnet ekonomi nasional.
*Kelompok yang Menolak atau Kritis
Kelompok ini, yang banyak berasal dari kalangan intelektual dan tokoh adat, menilai konsep “rumah bersama” masih mengandung bias struktural. Argumennya sederhana: bagaimana mungkin bicara rumah bersama, jika penghuni aslinya masyarakat adat Amungme dan Kamoro masih belum diakui secara hukum atas tanah ulayat dan wilayah adat mereka sendiri?
Mereka mengkhawatirkan bahwa frasa ini, jika tidak dibarengi dengan perlindungan hak adat dan pengakuan regulatif, justru menjadi alat untuk menormalkan asimilasi dan menghapus ketimpangan historis yang belum diselesaikan.
Jika dilihat secara objektif, kedua sudut pandang ini memiliki alasan yang sah. Mereka yang mendorong kebersamaan, tentu bergerak dari realitas sosiologis bahwa Mimika telah menjadi rumah bagi banyak orang. Di sisi lain, mereka yang menuntut keadilan historis juga berdiri di atas fakta hukum bahwa pengakuan masyarakat hukum adat masih lemah, dan belum ada regulasi daerah yang melindungi secara formal eksistensi Amungme dan Kamoro.
Artinya, perdebatan ini bukan soal siapa yang benar atau salah, tapi soal ketimpangan posisi dalam menyusun masa depan bersama. Gagasan “rumah” akan selalu dipertanyakan jika tidak dijelaskan: siapa tuan rumahnya? apakah ia diundang? atau digeser perlahan dari ruang tamu ke halaman belakang?
Kesimpulannya adalah Konsep “Mimika sebagai Rumah Bersama” patut diapresiasi sebagai upaya membangun narasi kolektif dan identitas kota modern. Namun, agar tidak menjadi sekadar slogan normatif, perlu dibarengi langkah-langkah nyata Pengakuan hukum terhadap masyarakat adat, Pemetaan wilayah ulayat, Penguatan lembaga adat dalam tata kelola daerah, dan Inklusi adat dalam agenda Smart City.
Hanya dengan cara itu, rumah bersama tidak hanya menjadi bangunan bersama, tetapi juga menjadi milik bersama yang adil, setara, dan dihuni dengan saling menghormati. (**)